Fimela.com, Jakarta "Travel brings power and love back into your life," satu ungkapan Jalaluddin Rumi ini mungkin bisa mengubah jalan hidup, filosofi, bahkan ego seseorang jika direnungkan dengan penuh kesungguhan. Berbingkai ratusan kisah penjelajahan dengan keterlibatan sejumlah 'tempat anonim', gerbang imaji akan perjalanan akbar pun dimulai.
Tak lagi soal memetakan puncak-puncak tertinggi Himalaya, pun bukan sebagai bentuk pemberontakan atas keteraturan lingkungan sosial. Seperti kebanyakan perihal, perjalanan juga tak luput dari dinamika. Sekarang, traveling merupakan bagian dari gaya hidup, bahkan tak jarang dijadikan sebagai penentu kelas sosial.

Advertisement
Baca Juga
Menjamurnya buku-buku perjalanan dengan beragam kemasan, baik 'contekan' itinerary, tips, serta yang bernuansa memoar, semua kerap dijadikan indikator traveling goals. Publikasi besar-besaran, limpahan pujian akan satu destinasi dari 'sejuta' sudut, dan jangan lupakan barisan aksara yang disusun sedemikian rupa agar menimbulkan rasa ingin tahu.
Alhasil, 'muaranya' berupa pantai perawan yang tak lagi jadi perawan, gundukan kertas di antara bentangan edelweis, serta plastik di tengah 'savana' koral beragam warna. Sadar atau tidak, arus informasi yang menerjang tanpa ampun akan jadi semacam dorongan untuk mencari pembuktian dari 'setumpuk' kegundahan berbalut penasaran.
Entah diiringi dengan kalimat apapun setelahnya, perjalanan hampir pasti dimulai dengan kuriositas. Tentang bagaimana rasanya 'tersesat' di jalan-jalan sempit kota kuno, berdiri di tanah yang lebih dekat dengan langit, juga dihadapkan dengan bentangan biru pekat samudra.

Berawal dari angan polos nan lugu, eksekusi mimpi tak selalu berlaku sama bagi setiap orang. Penutupan salah satu pulau tropis cantik, Koh Tachai, jadi bukti konkrit. 'Berbaring' di laut Andaman, surga bahari yang dikenal dengan air laut sebening kristal dan hamparan pasir putih itu diselamatkan pemerintah Thailand dari garangnya serbuan turis.
Kalau ingin bercermin lebih dekat, sejumlah tempat di Indonesia pun telah sukses dicarut-marutkan para 'tamu'. Ketika menulis artikel ini, saya seakan kembali menyesap pergantian aroma laut ketika perahu kayu mendekati Kaliadem di utara Jakarta. Jangan bertanya tentang seberapa tak sedap, karena sungguh keadaan itu lebih membuat saya miris daripada jijik.
Pun dengan 'adegan' plastik yang mengapung di perairan Taman Nasional Karimunjawa. Benda bening itu bak alien di bingkai pemandangan saya yang sudah dipenuhi biru laut utara Jawa. "Ayo siapa yang buang sampah sembarangan?" tanya nakhoda kapal kala itu sebelum akhirnya menceburkan diri dan mengambil plastik tersebut.
Advertisement
Bisakah Publikasi Tak Berbanding Lurus dengan Perusakan?
Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, namun orang-orang tak bertanggung jawab yang melabelkan diri sebagai traveler atau apapun itu, nyata adanya. Entah acuh atau mereka tak pernah membaca dan tersentuh pada untaian kata, "leave nothing but footprints, take nothing but memories."
Meski demikian, saya pun tak bisa menampik kalau perkenalan suatu tempat dengan turis akan bermanfaat bagi banyak pihak. Dari yang paling luas, yakni negara, hingga masyarakat lokal untuk skala sempitnya. Belum lagi membahas soal pertukaran cara berpikir dan pemaknaan kearifan lokal yang bisa berguna dalam cangkupan lebih besar.

Advertisement
Namun, sampai kapan pertukaran ini harus dibayar dengan harga mahal? Terlalu mahal bahkan. Fenomena yang terjadi belakangan mungkin akan menciptakan tanya, "apakah publikasi sepadan dengan kerusakan yang akan ditimbulkan setelah 'ia' dikenal dunia?"
Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab pihak yang memperkenalkan? Penulis buku? Awam? Jurnalis? Sampai sejauh mana komunikator bisa mengatur pemahaman dan pemaknaan komunikan? Jika menerapkan 'teori' stimulus-respons, 'beban' tak bisa hanya diletakkan di satu pundak.
Sebagai penulis, himbauan dalam bentuk persuasi sudah mulai diterapkan. Di samping itu, sudah banyak juga travelmate yang saling mengingatkan untuk bersimbiosis mutualisme dengan alam. Publikasi seharusnya bukan hanya tentang 'menjual', namun juga bagaimana memelihara, bahkan kalau perlu memunculkan sense of belonging.
Tak ada yang bilang mudah, mungkin malah harus ada sedikit paksaan di sini. Menerapkan pembatasan pengunjung seperti yang diberlakukan Pantai Tiga Warna di Malang, misalnya. Mungkin dengan kesan sulit mendapatkan, maka kunjungan ke tempat tersebut akan lebih dihargai.
Namun tentu saja, sekeras apapun aturan, pengambilan keputusan tetap ada dalam diri. Perjalanan itu sebenarnya bersifat sangat pribadi. Perihal seseorang menjalin komunikasi bersama semesta, memperlakukannya seperti ia mau diperlakukan. Mendengar setiap pesan yang hendak disampaikan, meski hanya lewat hembusan angin pesisir.
Jika saya boleh menginterpretasikan kalimat Lao Tzu, "the futher one goes, the less one know," traveling sangat mampu memberi makna yang tak bisa diajarkan oleh apa dan siapapun. Hingga menemukan 'formula' agar publikasi tak selalu berpangkal pada buruk rupanya satu destinasi, mari bersama melihat semesta tak hanya dengan mata, namun juga rasa.
Asnida Riani,
Editor Kanal Style Bintang.com
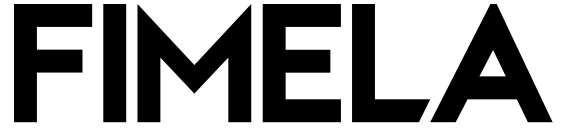
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/342404/original/092152600_1628159793-unnamed.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1248990/original/074911200_1464595252-1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4808801/original/013639400_1713764917-shutterstock_2185337765.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4806360/original/034427700_1713501365-Snapinsta.app_439314984_18433241236015031_5745407475061076742_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3270031/original/049652200_1602908541-traveling.jpg)
![[Gempur M Surya/Liputan6.com]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/PRJCgUV6qLowFWAzuMOUeZmEvKY=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4698013/original/015659700_1703553176-Potrait_1706x1280px_Aliya_Amitra_6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4665437/original/009101300_1701131245-0E6A8192-01_wm.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4629661/original/037153500_1698716782-IMG_9795_wm.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4614129/original/087807400_1697543308-IMG_0180.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4588432/original/088178300_1695690859-IMG_5541_wm.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4554996/original/046090200_1693270424-3L4A4355_wm.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4805047/original/021019000_1713421265-FIMELA_FASHION_-_ELEGANCE_IN_EVERY_STITCH.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4788875/original/001795800_1711748916-Web_Photo_Editor_-_2024-03-30T044734.726.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4787452/original/063780400_1711609467-FIMELA_FASHION_-_FAITH_IN_ELEGANCE__LS.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4757823/original/006595500_1709202782-FIMELA_FASHION_-_REFINE_YOUR_STYLE__IG_FEED.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4701815/original/002683400_1703842292-FIMELA_FASHION_-_GLAM_IT_UP_WITH_GIVENCHY__LS__prev.jpg)
![Beberapa seleb atau public figure mendapat kesempatan untuk datang ke JCC menyaksikan debat Cawapres berlangsung. [@thariqhalilintar/@fero_walandouw/@iben_ma]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/4LmITakKGG6DsSTP68MKBTR9h8w=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4696314/original/059781700_1703307951-WhatsApp_Image_2023-12-23_at_11.47.10.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4750084/original/077124500_1708590834-Fimela_Fame_Story_-_IDGITAF_VIRAL_ITU_BONUS__IG_Feed.jpg)
![Famestory Nirina Zubir. [Foto: Adrian Putra/Fimela]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5PZ6O0fMbngf4wg8b0lulaNdVsI=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4690941/original/086525200_1702951456-Nirina_Zubir.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4656877/original/034172000_1700545070-Fimela_Fame_Story_-_MARCELLO_TAHITOE_DUNIA_MENGUBAH_HIDUPKU__IG_Feed__prev.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4656391/original/078786300_1700499515-Marcello_Tahitoe.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4621773/original/007408000_1698124064-Fimela_Fame_Story_-_TINA_TOON_POLITIK_ITU_SERU___IG_Feed__prev.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4621233/original/029451700_1698069730-Potrait_1706x1280px_fame_Story_Tina_Toon_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4792546/original/033965100_1712112301-shutterstock_2320006321.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4794990/original/076180700_1712287541-shutterstock_2202866437.jpg)
![Indah Nada Puspita buktikan perempuan bisa bermimpi tanpa batas. [Dok/Adrian Utama P]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/p0CGSd8qKVswJfYMgF9GQTjVww0=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4791062/original/008615200_1711977261-0E6A1300-01.jpeg)
![Tini Sardadi, Founder ARTKEA dan Atya Sardadi. [Foto: Document/ARTKEA]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/S16McTPwgHW8bU8C5AJx-bgvwWY=/0x1553:4480x4078/320x217/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4789901/original/006756600_1711879096-ARTKEA_FOUNDERS_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4789430/original/024708900_1711819844-Snapinsta.app_382522712_674997674569025_287944984469016921_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4788927/original/049547700_1711766567-190452490_964522600962671_7372987768112641533_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4795894/original/043639700_1712330325-shutterstock_1476929348.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3901151/original/099776500_1641960775-shutterstock_1827134267.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4788995/original/056979800_1711772061-fried-chicken-with-red-green-chili-peppers-onion-plate.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4810502/original/067200400_1713869684-Belajar_Bersama_Memperbaiki_Pakaian_bersama_Bev_Tan__Mulih_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4807798/original/094971400_1713667846-shutterstock_2147435219.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3082213/original/084290700_1584764526-shutterstock_1385399636.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3981470/original/082823400_1648781672-shutterstock_1951678480.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3526681/original/098428000_1627698621-shutterstock_1979543048.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3421823/original/051732900_1617768255-putri_salju_lumer.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4787217/original/027727500_1711597598-pexels-fauxels-3184187.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4791067/original/049651900_1711977504-WhatsApp_Image_2024-04-01_at_19.39.12.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4772441/original/060119400_1710407444-pexels-roman-odintsov-5836986.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2403999/original/011349100_1541743261-shutterstock_1134556445.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2881034/original/092358400_1565750672-resep_urap_HL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4795894/original/043639700_1712330325-shutterstock_1476929348.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4810724/original/060733200_1713881110-439293346_408973205266200_3310946756904875340_n.jpg)