Fimela.com, Jakarta Hubungan antara ibu dan anak perempuan memiliki ruangnya sendiri yang penuh warna—kadang hangat dan penuh pelukan, kadang juga dipenuhi perbedaan pandangan yang membuat keduanya saling menjauh untuk sementara waktu. Meskipun demikian, sekeras apa pun pertengkaran atau seberapa besar jarak yang sempat tercipta, selalu ada cinta yang tak bisa tergantikan, kasih sayang yang kerap tersembunyi dalam tindakan-tindakan sederhana yang mungkin tak pernah diucapkan. Kedekatan emosional itu tumbuh bersama waktu, mengakar dalam hati, bahkan ketika sering kali tak disadari secara langsung.
Maka saat perpisahan atau kehilangan datang, kesedihan yang dirasakan menjadi sangat mendalam. Bukan hanya karena tak lagi bisa melihat atau mendengar sang ibu, tetapi juga karena hilangnya cermin tempat anak perempuan selama ini belajar mengenal diri. Crying in H Mart karya Michelle Zauner mengisahkan perasaan kehilangan itu dengan begitu jujur dan menyentuh. Memoar ini tidak hanya bercerita tentang duka karena kehilangan seorang ibu, tetapi juga tentang bagaimana kenangan, terutama lewat makanan, menjadi jembatan paling setia yang menghubungkan cinta dan identitas.
Advertisement
Advertisement
Blurb Crying in H Mart
Judul: Crying in H Mart
Penulis: Michelle Zauner
Alih bahasa: Devina Heriyanto
Desain sampul: Martin Dima
Setting: Fajarianto
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
***
"Cintanya lebih kokoh daripada cinta yang kokoh. Brutal, sekuat baja. Cinta yang keras dan tidak ada ruang untuk kelemahan satu senti pun. Cinta yang melihat apa yang terbaik untuk kita sepuluh langkah ke depan, dan tidak peduli jika sakitnya luar biasa dalam perjalan perjalanan ke sana. Ketika aku terluka, ibuku juga merasakannya sedalam-dalamnya, seakan-akan dia sendiri yang merasakan nyerinya. Dia merasa bersalah karena terlalu peduli. Aku menyadari ini sekarang, ketika mengenang masa lalu. Tidak ada orang di dunia ini yang akan mencintaiku seperti ibuku, dan dia tidak akan membiarkan aku melupakannya." (hlm. 19)
"Aku berpikir apakah aku harus berusaha menjelaskan betapa pentingnya ini buatku. Bahwa memasak makanan ibuku telah menjadi semacam pertukaran peran yang absolut, sebuah peran yang ingin kujalani. Bahwa makanan adalah bahasa tak terucap di antara kami, bahwa makanan menyimbolkan bersatunya kami kembali, ikatan kami, kesamaan minat kami." (hlm. 115)
"Duka, seperti depresi, membuat hal-hal sederhana jadi sulit." (hlm. 204)
"Aku mulai membuat kimchi sebulan sekali, sebagai terapi baruku." (hlm. 254)
***
Dalam memoar ini, Michelle Zauner—yang dikenal sebagai vokalis dari Japanese Breakfast—mengajak kita menyelami cerita hidupnya sebagai perempuan Korea-Amerika yang tengah menghadapi kepergian sang ibu karena kanker.
Cerita dibuka dengan momen emosional: Michelle menangis di tengah H Mart, sebuah supermarket Asia yang penuh dengan barang-barang yang mengingatkannya pada sang ibu. Tangis itu bukan sekadar sedih karena kehilangan, tapi juga karena perasaan keterpisahan dari budaya dan warisan yang selama ini diwakili ibunya.
Yang membuat memoar ini begitu kuat adalah penggunaan makanan sebagai simbol ingatan dan cinta. Di setiap lembar, kita akan menemui kisah tentang kimchi buatan tangan, sup rumput laut di hari ulang tahun, mie jajang, dan berbagai hidangan Korea lainnya yang bukan hanya sekadar makanan, tapi juga bentuk kasih sayang yang disampaikan tanpa banyak kata. Melalui proses memasak, Michelle mencoba menyatukan kembali serpihan-serpihan dirinya yang tercerai-berai setelah kepergian sang ibu.
Tidak semua hubungan ibu dan anak ditampilkan secara manis dalam buku ini, dan justru di sanalah letak kejujuran yang menyentuh hati.
Michelle tidak menyembunyikan betapa sulitnya berkomunikasi dengan ibunya yang tegas dan memiliki ekspektasi tinggi. Tapi di balik benturan-benturan itu, tersimpan cinta yang sangat dalam.
Buku ini menyuarakan bahwa cinta tidak selalu tampil dalam kelembutan, tapi bisa juga dalam bentuk ketegasan, pertengkaran, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membentuk kehidupan.
Kehilangan ibunya memunculkan satu kesadaran pahit dalam diri Michelle bahwa ia merasa semakin jauh dari akar budaya Koreanya. Ibunya adalah satu-satunya penghubung kuat dengan tradisi, bahasa, dan nilai-nilai Korea.
Ketika sang ibu tiada, Michelle seperti kehilangan sebagian besar dari siapa dirinya. Proses mengenang ibunya pun berubah menjadi perjalanan menyentuh untuk menemukan kembali identitas yang sempat hilang, sambil membangun koneksi baru dengan masa lalu yang belum sempat ia pahami sepenuhnya.
Sahabat Fimela, buku ini juga sangat menyentuh karena memperlihatkan bagaimana kesedihan dan kedukaan bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam hitungan waktu. Ketika ia bepergian ke Vietnam bersama sang ayah dengan harapan bisa memulihkan diri dari rasa duka setelah kepergian sang ibu, ada hal-hal baru yang ia sadari. Rasa duka pun ia maknai dengan sudut pandang yang baru.
Michelle menggambarkan duka sebagai teman lama yang datang tanpa diundang dan tidak pernah benar-benar pergi. Tapi justru dari kedukaan itu, ia belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan menerima bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang.
Di tengah rasa kehilangan yang besar, Michelle menulis dengan gaya yang begitu jujur dan penuh detail. Dari setiap untaian katanya, dia membawa kita masuk ke ruang-ruang paling pribadi dalam hidupnya: kamar rumah sakit, dapur tempat ibunya memasak, hingga lemari es tempat bahan-bahan masakan Korea disimpan dengan penuh cinta. Setiap pengalaman yang ia bagi terasa hidup, karena ditulis untuk menyampaikan apa adanya tentang rasa sakit dan kekuatan.
Buku ini pun menjadi refleksi yang mendalam tentang bagaimana seseorang bisa tetap terhubung dengan orang yang dicintainya, bahkan setelah mereka tiada.
Michelle memperlihatkan bahwa hubungan dengan orang yang telah pergi tetap bisa tumbuh, yaitu lewat kenangan, lewat masakan, lewat hal-hal kecil yang terus hidup dalam keseharian. Buku ini seolah menyuarakan bahwa duka tidak harus memisahkan, justru bisa menjadi jalan untuk mengenal cinta yang jauh lebih dalam.
Ada kesedihan yang begitu menyayat perasaan ketika Michelle harus membereskan barang-barang mendiang ibunya. Dia menemukan kepingan-kepingan kenangan masa kecil yang selama ini disimpan sangat baik oleh sang ibu. Ketika satu demi satu barang ia rapikan dan pilah lagi, berbagai perasaan kembali menyeruak dan menghadirkan pengalaman yang begitu dalam.
Lebih dari sekadar kisah pribadi, Crying in H Mart juga menyentuh banyak hati karena mewakili pengalaman banyak orang yang merasa hidup di antara dua dunia: antara budaya asal dan budaya tempat mereka tumbuh. Michelle mewakili suara anak-anak yang sering kali merasa tidak cukup "ini" dan tidak cukup "itu", dan yang hanya menyadari pentingnya akar ketika akar itu telah hilang. Menyikapi orang-orang di sekitarnya yang menganggapnya aneh atau berbeda juga bukan hal yang mudah. Terlahir dari Ayah berdarah Amerika dan Ibu berdarah Korea Selatan, Michelle memiliki masa-masa di mana dia pernah terluka soal bagaimana orang-orang di sekitarnya menyikapi identitasnya.
Gaya penulisan Michelle begitu luwes dan puitis tanpa menjadi berlebihan. Ia tahu kapan harus berbagi luka, kapan harus membuat kita tersenyum lewat ingatan-ingatan kecil yang hangat. Tulisannya tidak menggurui, tapi mengajak untuk merenung bersama. Seperti sahabat lama yang duduk dan bercerita dengan tenang, ia menuntun kita memahami makna kehilangan, kerinduan, dan pentingnya mengenal jati diri.
Sahabat Fimela, jika kamu tengah mencari buku yang tidak hanya indah secara bahasa tapi juga kaya makna, Crying in H Mart bisa masuk ke daftar bacaanmu yang berikutnya. Memoar ini memuat kisah tentang kasih seorang ibu, tentang rasa duka yang jujur, dan tentang cinta yang tetap hidup dalam kenangan. Buku ini akan menyentuh hatimu, mengajarkanmu untuk menghargai hal-hal kecil, dan mungkin juga mengajarkan bahwa tidak apa-apa menangis di tengah keramaian, karena di sanalah, kita sering kali paling terhubung dengan yang paling kita cintai.
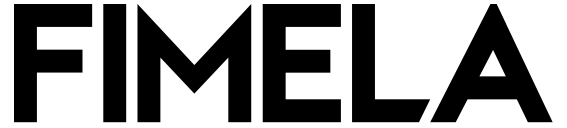
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/1783547/original/015968300_1743066229-WhatsApp_Image_2025-03-27_at_16.01.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5264744/original/053529500_1750901301-WhatsApp_Image_2025-06-26_at_08.21.42.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5264745/original/073671800_1750901420-WhatsApp_Image_2025-06-26_at_08.21.43.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5465029/original/070699400_1767756811-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share__1_.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5418673/original/032439000_1763624709-high-angle-womens-having-lunch.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5501566/original/058091000_1770946817-Depositphotos_641265014_L.jpg.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5501555/original/058613600_1770945749-Depositphotos_855475316_L.jpg.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5501560/original/049832000_1770946269-Depositphotos_189857102_L.jpg.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5494109/original/059955800_1770278846-Depositphotos_467200236_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5492159/original/054788400_1770124951-WhatsApp_Image_2026-02-03_at_18.27.37.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5494164/original/091572400_1770279846-Depositphotos_389184090_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5499280/original/056469900_1770781913-cropped-e866d747-e2cb-4ec4-b44f-acea415c6cc6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5492144/original/066339500_1770124140-WhatsApp_Image_2026-02-03_at_18.27.37__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5490699/original/021266800_1770021961-Depositphotos_321262424_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5490684/original/052362200_1770021120-Depositphotos_301379960_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5442171/original/068778500_1765530125-pexels-limoo-3859717-16759203.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5510178/original/013421200_1771821333-Depositphotos_683567022_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5510096/original/071607900_1771817715-Depositphotos_363371356_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5510059/original/042278300_1771816221-Depositphotos_393327954_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5509993/original/047801700_1771813274-Depositphotos_852451116_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5476903/original/007343100_1768802523-WhatsApp_Image_2026-01-19_at_12.38.19.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5516233/original/082177400_1772268178-TB_SPR26_RAMADAN_CAMPAIGN_20261299.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5516221/original/081545200_1772267352-Screenshot_2026-02-28_152018.jpg)
![Sahabat Fimela, ikan kukus jahe kurma dapat menjadi menu buka puasa yang hangat dan pas untuk berbuka. [Dok/freepik.com/jcomp]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/nkTiMCvOnxERQjCjv9HfzmcdLeo=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5511876/original/007087500_1771919613-25388.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5516197/original/068081400_1772265559-WhatsApp_Image_2026-02-27_at_23.05.31__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5456439/original/034486400_1766886922-IMG-20251201-WA0005_1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515377/original/037610500_1772173019-AFP__20260226__992C4Q2__v1__HighRes__BritainRoyals.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5511032/original/064378000_1771861434-2.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5504505/original/044507100_1771238995-80299.jpg)
![Tidak hanya menjadi destinasi fashion eksklusif, pavilion seluas lebih dari 1.800 meter persegi ini juga memperlihatkan bagaimana dunia luxury mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih dekat dengan alam dan keberlanjutan. [Dok/DIOR].](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/uNmGHFL-mnf9vwtYfYBHO0QssKw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5510359/original/082447300_1771826792-WhatsApp_Image_2026-02-23_at_12.47.36__3_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5481259/original/043313700_1769083787-Tarian_Kecak_di_Sanggraloka_Ubud.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2777881/original/092225500_1555166618-lasse-moller-1360248-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3977835/original/066021800_1648524608-pexels-ahmed-aqtai-2233416_1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5275206/original/016619700_1751868718-mother-daughter-studying-alphabet.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5490544/original/098026000_1770015413-Depositphotos_506933790_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5457669/original/070899100_1767013830-woman-with-stomachache-puts-her-hands-her-stomach-covers-her-mouth.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3917538/original/022218100_1643350868-henry-co-yxfGrQvLzJo-unsplash_1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5325365/original/031645100_1755963944-front-view-young-female-red-shirt-suffers-from-physical-threats-violence-light-space-female-cloth-photo_11zon.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5298500/original/084082800_1753763943-yael-gonzalez-oV6RSDQlq8Q-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5327417/original/054956200_1756180723-giu-vicente-pYrS9SgBLk0-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4917542/original/074860100_1723604268-pexels-vanessa-loring-5083228.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5250058/original/018575800_1749706430-batik_balita.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3591671/original/053834000_1633322807-insung-yoon-iioAHjNYA_o-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5327421/original/068931400_1756180732-michal-parzuchowski-geNNFqfvw48-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5132670/original/074184800_1739499905-IMG_3555.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020257/original/010074600_1732515505-IMG_0206.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5479072/original/041763200_1768967463-raychan-YT1LV3U4ViA-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5477296/original/044809300_1768815162-pexels-yi-ren-57040649-25551423.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5477191/original/015898700_1768811410-pexels-olly-3807757.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5477138/original/069417700_1768809895-pexels-yi-ren-57040649-34990362.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515652/original/027031200_1772183970-tangga_Stasiun_Depok_Baru.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515822/original/040288400_1772191679-Guru_dan_teman_kelas_STN_menyalakan_lilin_di_meja.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515640/original/070632700_1772182819-1001042758.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515388/original/034478200_1772173258-Penyelundupan_daging_ilegal_di_Kepri.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515475/original/095872500_1772176644-Gubernur_Kaltim_Rudy_Ma_sud.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515350/original/091433200_1772171359-Bandar_Narkoba_Koko_Erwin_Ditangkap_Polisi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5516233/original/082177400_1772268178-TB_SPR26_RAMADAN_CAMPAIGN_20261299.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5516221/original/081545200_1772267352-Screenshot_2026-02-28_152018.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5219318/original/067676500_1747211347-000_46JX8ZP.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5510174/original/095977000_1771820789-Depositphotos_408201428_XL.jpg)