Fimela.com, Jakarta Kepergian Muhammad Ali menyisakan tangis dan kesedihan bagi para penggemarnya. Bukan hanya pecinta olahraga tinju, tapi para Generasi X yang hidup di sepanjang masa kejayaannya pun turut berduka. Meski mungkin tak pernah mengikuti pertandingannya, baik di TV ataupun secara langsung.
Saya yang lahir tahun 90-an memang tak begitu mengenal sosoknya. Memang, dulu kerap menonton pertandingan tinju di TV setiap hari Minggu siang, usai tayangan kartun yang maraton dari subuh hingga jam makan siang.
Baca Juga
Tapi tetap saja saya tak mengenal Ali. Saya hanya mengenalnya lewat sebuah film dokumenter, yang membuat saya entah berapa lama terbengong-bengong dengan sosok The Greatest dalam layar kaca. Saya lantas kembali bertemu Ali lewat sebuah poster yang saya temukan di sebuah gudang rumah nenek saya dulu. Dulu masih belum kenal siapa Ali.
Tapi entah kenapa, ada magnet yang saat itu menarik perhatian saya pada sosok ber-boxer dengan sarung tinju itu. Matanya. Ali seperti memandang saya lekat-lekat. Pandangan matanya bukan seperti menakuti anak umur 10 tahun. Tapi seperti bertanya, “siapa kamu sebenarnya?” Di samping kanan sosoknya yang berdiri dengan pose khas seorang petinju, ada sebaris kata yang saat itu belum sanggup saya pahami. “Float like a butterfly, sting like a bee.”
Advertisement

Saya lantas tumbuh tanpa bayang-bayang pertandingan Ali. Namun, 14 tahun kemudian, ketika mendengar kabar kepergiannya, pandangan mata itu kembali muncul dalam benak. Pertanyaan yang sama kembali terngiang. “Siapa kamu sebenarnya?” Menjawab pertanyaan itu tidak mudah. Tidak untuk anak berumur 10 tahun. Tidak juga bagi perempuan berumur 24 tahun. Tergelitik oleh pertanyaan yang tak kunjung pergi selama 14 tahun itu, saya lantas mulai mencari tahu lebih banyak tentang Ali.
Ternyata, sosok Ali bukan hanya dikenal sebagai petinju hebat. Tapi juga sebagai sosok pejuang kesetaraan bagi orang-orang berkulit hitam di Amerika. Pikiran saya langsung terlempar pada kisah, di mana Ali sempat diusir dari sebuah restoran. Hanya lantaran dia berkulit gelap.
Ali lantas bertekad untuk menjadi bintang di dalam ring tinju. Salah satu tujuannya, menjadi juara dunia, sehingga suara yang dia keluarkan akan didengar banyak orang.

Menjadi legenda tinju dunia membuatnya banyak dikagumi orang. Termasuk saya, meski saat itu belum begitu mengenalnya. Bagaimana tidak, dia pemegang sabuk juara dunia kelas berat tinju tiga kali. Tiga kali! Dari 56 pertandingan, dia cuma kalah 5 kali. Dia menang melawan para jagoan tinju seperti Sonny Liston, George Foreman, dan Joe Frazier.
Merasakan energi kehebatan The Greatest, saya lantas jadi penasaran, apa yang membuatnya benar-benar menjadi bintang tinju. Saya tonton ulang videonya saat bertanding dalam ring. Saya bandingkan dengan cara lawannya bermain.
Tanpa terlalu peduli dengan siapa lawannya, saya menemukan satu perbedaan yang jelas dalam beberapa pertandingan itu. Ali bertarung dengan kedua tangan terjulur di kedua sisi tubuhnya. Bukankah seharusnya petinju selalu melindungi wajah dan kepala?
Advertisement
Biarkan Tekad Muhammad Ali Tetap Membara dalam Jiwa Muda
Dalam suatu kesempatan, saya lantas bertemu dengan salah satu teman dekat. Dia termasuk dalam Generasi X yang tumbuh seiring dengan kegemilangan karier Ali. Dia ‘kenal’ Ali. Dia bilang, “Ali bukan petinju hebat. Banyak petinju kelas dunia lain menyarankan orang untuk tidak bertarung seperti Ali. Dia gila! Dia sama sekali tidak melindungi wajah dan kepalanya.”
Keesokan harinya, saya kembali tonton video yang sama. Ya, tidak ada yang bermain sepertinya. Bukannya melindungi diri, dia malah membiarkan lawan memukulnya hingga dia terpojok pada pinggir ring. Tapi, usai sang lawan kehabisan tenaga, dia balas melawan. Di situ, baru saya mengerti strategi Ali saat berada di dalam ring.
Tapi bukan itu yang membuatnya pantas disebut sebagai yang terhebat. Ali bukan hanya pandai bertaktik. Tapi juga memainkan kata dan merangkainya menjadi rentetetan kalimat berbobot. Dia bukan hanya melawan para tandingannya di dalam, tapi juga di luar ring.
Seperti sebelum bertanding dengan Sonny, dia mengatakan “if you like to lose your money, be a fool and bet on Sonny.” Ada juga satu kalimat yang menggugah, seperti saat melawan George Foreman, “float like a butterfly, sting like a bee, his (George) hands can’t hit what his eyes can’t see.”

Setiap pertandingan, bukan cuma soal menang atau kalah. Tapi dia memiliki tujuan pada setiap pertandingannya. Seperti dilansir dari sebuah media nasional, Ali pernah berkata, “aku selalu memiliki tujuan setiap kali naik ring. Aku harus menjadi juara. Dengan menjadi juara, aku lebih mudah memperjuangkan hak-hak kaumku dan membantu orang lain.”
Artinya, dalam setiap perjalanannya menuju kesuksesan, dia selalu memiliki target yang jelas. Juga dengan alasan yang pasti. Ali selalu berjuang bukan cuma demi dirinya sendiri, tapi juga demi orang lain. Ali yang tadinya saya pikir sombong lantaran memanggil dirinya sendiri sebagai The Greatest, kini berubah menjadi idola.
Namun, selepas kepergian Ali, orang hanya mengenangnya sebagai petarung tanpa ampun. Padahal, Ali lebih dari hanya sekadar petinju dan pembela hak kaum-kaumnya. Esensi pertarungan dan perjuangan Ali seharusnya bisa tertanam dalam diri setiap orang. Terutama milenials yang masih mencari arah dan tujuan hidup.
Ali mungkin bukan contoh petarung yang baik. Tapi di balik gayanya yang berbeda dengan petinju lain saat di atas ring, The Greatest membuktikan bahwa kesuksesan tak selalu mensyaratkan teknik. Tapi juga ada strategi dan taktik. kecerdasan dan kecerdikan dalam melihat situasi. Tujuan bukan hanya dilafalkan untuk satu perjalanan hidup yang panjang. Tapi juga dalam setiap langkah menuju target impian.

Ali bukan hanya seorang idola. Terlepas dari segala rumor dan agama yang dipeluknya, Ali juga merupakan guru. Jasadnya mungkin tak lagi bernyawa. Kedua tangannya tak lagi sanggup mengepal dan menjatuhkan sederet lawan. Tapi ayunan tinjunya, derap langkahnya di atas ring masih hangat terdengar dan tergambar jelas dalam benak.
Sosok Ali belum mati. Dia bukan hanya mengajarkan semua orang bagaimana menjatuhkan lawan. Tapi juga menunjukkan apa artinya kasih sayang saat membela kaumnya yang tertindas di Amerika Serikat. Ali bukan hanya bintang yang kerap disebut-sebut ayah saya ketika saya masih duduk di pangkuannya. Tapi juga sebagai orangtua kedua bagi setiap anak muda. Dia bukan bertarung. Dia mengajarkan banyak arti hidup dengan setiap konsekuensinya. Meski belum menemukan jawaban yang ‘ditanyakan’ Ali, tapi saya menemukan eksistensinya dalam diri.
Jangan kubur Muhammad Ali dalam-dalam. Biarkan derap langkahnya masih terdengar tiap kali menutup mata. Biarkan napasnya tetap berembus hangat. Agar terus hidup dalam diri setiap anak muda, dengan segenap semangat dan keyakinannya untuk sukses dan menyukseskan orang lain.
Karla Farhana,
Editor Feed Bintang.com
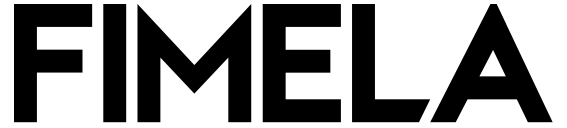
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/351016/original/021495500_1436056011-AkXoOdTcG-18WQxjC_ZSS1ipEecOqNRANZDdqe9zK4qZ__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1254637/original/060941600_1465035090-7_000_ARP3037592.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5465029/original/070699400_1767756811-Lagidiskon__desktop-mobile__356x469_-_Button_Share__1_.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5494109/original/059955800_1770278846-Depositphotos_467200236_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5492159/original/054788400_1770124951-WhatsApp_Image_2026-02-03_at_18.27.37.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5494164/original/091572400_1770279846-Depositphotos_389184090_S.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5499280/original/056469900_1770781913-cropped-e866d747-e2cb-4ec4-b44f-acea415c6cc6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5492144/original/066339500_1770124140-WhatsApp_Image_2026-02-03_at_18.27.37__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5490699/original/021266800_1770021961-Depositphotos_321262424_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5490684/original/052362200_1770021120-Depositphotos_301379960_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5442171/original/068778500_1765530125-pexels-limoo-3859717-16759203.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5442156/original/026841000_1765529263-pexels-andrew-4134788.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5442413/original/013612100_1765536532-pexels-towfiqu-barbhuiya-3440682-25946547.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5440854/original/016558400_1765446104-pexels-shvets-production-9775111.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5440792/original/025532900_1765444712-pexels-karola-g-8547628.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5276597/original/051980800_1751957317-peter-kalonji-LH74lRYvBY4-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5502025/original/015552500_1770965883-SnapInsta.to_626778566_18101542837846478_5069684385827042858_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5501641/original/038460000_1770951026-Depositphotos_637281758_XL.jpg)
![Cara Membuat Rutinitas Beauty Lebih Ramah Lingkungan, Simpel dan Tetap Nyaman Dijalanin. [Dok/pexels/ron lach].](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Bir9w1lISxTUIaUAvUnDAGUZXuc=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5500011/original/050984900_1770806410-pexels-ron-lach-8142198.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4909653/original/076612200_1722839219-pexels-greta-hoffman-9475421.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5497350/original/008176000_1770625488-Screenshot_2026-02-09_085913.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5132670/original/074184800_1739499905-IMG_3555.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020257/original/010074600_1732515505-IMG_0206.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5479072/original/041763200_1768967463-raychan-YT1LV3U4ViA-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5477296/original/044809300_1768815162-pexels-yi-ren-57040649-25551423.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5477191/original/015898700_1768811410-pexels-olly-3807757.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5477138/original/069417700_1768809895-pexels-yi-ren-57040649-34990362.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5275206/original/016619700_1751868718-mother-daughter-studying-alphabet.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5490544/original/098026000_1770015413-Depositphotos_506933790_XL.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5457669/original/070899100_1767013830-woman-with-stomachache-puts-her-hands-her-stomach-covers-her-mouth.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3917538/original/022218100_1643350868-henry-co-yxfGrQvLzJo-unsplash_1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5325365/original/031645100_1755963944-front-view-young-female-red-shirt-suffers-from-physical-threats-violence-light-space-female-cloth-photo_11zon.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4015359/original/003887100_1651889392-jose-ibarra-ifM0755GnS0-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3467177/original/055995500_1622181538-omar-lopez-zsXDWzlqpKU-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5364607/original/012717400_1759120770-standret.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5327421/original/068931400_1756180732-michal-parzuchowski-geNNFqfvw48-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4707585/original/088540000_1704514794-perfect-snacks-LIfFgPaO2w0-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446771/original/092213400_1765941318-close-up-happy-family-traveling.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5388215/original/089456400_1761115012-IMG-20251022-WA0009.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5497383/original/073624200_1770627074-chanel_plaza-indonesia_chanel-5-LD.jpg)
![Di lebaran hari ke 2, BCL, Noah, dan suaminya tampak mengenakan baju lebaran warna abu-abu. Semakin menarik dengan motif tulisan aksara. Noah dan ayah sambungnya kompak mengenakan atasan kemeja lengan pendek.[@itsmebcl]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/C3eTZLFFd8HPN6Y5YntA2eDJ1Yg=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5179409/original/072256100_1743563358-IMG_9001.jpeg)
![Penampilan elegan Yoriko Angeline kenakan lace dress warna dark grey dengan detail batwing sleeve 3/4. [@yorikooangln_]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/kI1oa7RvHF8PRqzl2W4lTzqatKw=/320x217/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4788846/original/046051600_1711744594-Snapinsta.app_434308408_1137998330891049_6905543376593062228_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5475707/original/045344200_1768642218-Aquazzura_Jakarta_Store_6.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5452876/original/099231900_1766461807-FIMELA_FASHION_-_Lanvin_at_Its_Most_Glam__IG_Feed__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3221935/original/084901000_1598605805-pexels-andrea-piacquadio-975250.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5504445/original/048553600_1771236764-pemilik_warung_duel_lawan_perampok.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4271014/original/025113500_1671800295-jakarta_light_festival-herman-5.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5504389/original/001005100_1771233965-evakuasi-korban-buaya.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2910533/original/077656200_1568366471-20190913_154149_resized.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5504346/original/069333800_1771233008-maling_hotel_mewah.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3446588/original/070754600_1620026864-Super_Air_Jet.jpg)
![Nasha Anaya Putri Pasha Ungu dan Okie Agustina Rayakan Ulang Tahun ke-17. [@nasha.anayaa]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/UKf3jqCFxctikLtlRt2RRNFYpGY=/0x41:926x563/260x125/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5504302/original/034706200_1771230881-IMG_5144_1_.jpeg)
![Beyonce Tampil dengan Rambut Pendek Bob Blonde. [@beyonce]](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/d0yN0uw1FShFK7u6Ewj4gVO5wx0=/80x80/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5504281/original/072922700_1771230236-IMG_5140_1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5276597/original/051980800_1751957317-peter-kalonji-LH74lRYvBY4-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5142928/original/035301500_1740478010-beauty-blogger-present-beauty-cosmetics-sitting-front-camera-recording-video.jpg)